YACOB Utama, Yakob Utama, Jacob Utama, Jakob Oetama.
Yang terakhir itu ejaan yang benar. Saya bernah bertanya langsung kepada beliau tentang ejaan nama beliau itu –saking banyaknya versi di media.
Beliau juga menjelaskan secara khusus bahwa kata "Oetama" di situ harus dibaca: utomo.
Beliau kan orang Jawa Tengah. Lahir di desa sekitar candi Borobudur. Bahwa ''utomo'' itu ditulis ''Oetama'' justru itulah yang benar –menurut grammar bahasa Jawa: bunyi "'o'' harus ditulis ''a'' manakala kata itu berubah bunyi ketika diberi akhiran ''ne''.
''Utomo'' ketika diberi akhiran ''ne'' bunyinya menjadi ''utamane''. Bukan ''utomone''.
Jangan disangka hanya bahasa Inggris yang grammar-nya bikin pusing. Cukup sampai di situ kita bicara bahasa Jawa.
Kita kan lagi membicarakan sosok hebat tokoh pers Indonesia yang meninggal Rabu siang kemarin: Jakob Oetama. Baca: Yakob utomo.
Saya tengah dalam perjalanan dari Surabaya ke Jakarta (pakai mobil) ketika staf di Kompas TV menghubungi saya.
Kompas TV minta agar saya ikut memberi kesaksian tentang Pak Jakob. Saya diminta menyiapkan HP dan laptop untuk pengambilan suara dan gambar.
"Saya tidak membawa laptop," jawab saya.
Lima menit kemudian saya baru tahu ada apa. Yakni setelah Joko ''Jagaters'' Intarto menghubungi saya: bahwa Pak Jakob meninggal dunia. Rabu, jam 13.00, di RS Mitra Keluarga, Jakarta.
Tentu saya tidak terlalu kaget. Saya sudah lama mendengar beliau sakit. Usianya juga sudah 89 tahun –beberapa hari lagi.
Saya langsung teringat semua kenangan lama. Pak Jakob adalah orang yang sabar, kalem, tenang, kalau berjalan tidak bergegas, kalau bicara lirih, ritme kata-katanya lamban dan wajahnya lebih sering datar –tidak bisa terlalu kelihatan gembira atau terlalu kelihatan sedih.
Pak Jakob, karena itu, adalah simbol sosok orang Jawa yang sangat sempurna. Kepindahan beliau ke Jakarta tidak membuat beliau berubah menjadi ''lu gue''. Tidak seperti saya: begitu pindah ke Surabaya langsung ikut menjadi bonek.
Kesantunan Pak Jakob itu mungkin karena budaya desa di Jawa Tengah sangat merasuk ke jiwanya. Mungkin juga karena roh Borobudur ikut mewarnainya. Mungkin sekali latar belakangnya sebagai guru masih terus terbawa. Mungkin pula kultur sekolah Seminari Katolik masih ada padanya –meski beliau tidak menyelesaikan seminarinya.
Rambut beliau lurus tapi dibiarkan agak panjang. Ibarat guru besar, Pak Jakob itu sempurna karena linier. Tidak seperti saya yang zig-zag: tamat SMA di Magetan langsung ke Kalimantan. Kawin pun dengan galuh Banjar, lalu jadi bonek, dan menjelang tua harus mengganti hati saya dengan hatinya orang Tionghoa dari Tianjin.
Pak Jakob adalah orang yang santun –santun yang linier. Dan itu tercermin dari gaya pemberitaan koran yang dilahirkannya: Kompas. Jurnalistik Kompas adalah jurnalistik yang santun. Terutama bisa dilihat dari Tajuk Rencananya. Yang bagi pengkritiknya dianggap sebagai tajuk dengan gaya yang muter-muter.
Di era saya muda, gaya Kompas seperti itu sangat menjengkelkan. Tidak radikal sama sekali. Tidak seperti Harian Kami-nya Nono Anwar Makarim yang dar-der-dor. Tidak seperti Harian Indonesia Raya-nya Mochtar Lubis yang memberontak. Atau tidak seperti Harian Nusantara-nya –aduh lupa siapa pemiliknya– yang menyerang-nyerang.
Keberanian Kompas yang paling berani –menurut anak-anak muda kala itu– hanyalah sebatas ini: menyindir.
Tapi ''Purwodadi kutane, sing dadi nyatane''. Maksudnya: yang penting kan kenyataannya. (Di kalimat peribahasa itu terdapat akhiran ''ne''. Maka kata ''kuto'' menjadi ''kuta'', ''nyoto'' menjadi 'nyata'').
Kenyataan adalah bukti yang paling tidak bisa diabaikan.
Kenyataannya: Kompas-lah yang paling hebat. Paling besar. Paling kaya. Kaya-raya. Harian Kami, milik ayah Nadiem Makarim itu, tewas dibredel.
Harian Nusantara, milik TD Hafaz, juga dibredel. Harian Indonesia Raya-nya Mochtar Lubis belakangan juga dibredel. Semua karena tidak mau tunduk pada kemauan penguasa.
Harian Kompas memang juga pernah dibredel. Tapi sangat sebentar –mungkin seminggu saja.
Koran saya dulu malah tidak pernah dibredel. Saya ikut gaya Pak Jakob yang sesekali harus mengalah –untuk menang. Lebih baik tetap bisa menyindir bertahun-tahun daripada sekali membentak lalu mati.
Waktu itu, perdebatan mana yang lebih baik –menyindir berlama-lama atau bisa membentak tapi hanya sekali– tidak pernah reda di kalangan wartawan saat itu. Topik perdebatan itu lebih disederhanakan: pilih jalan Mochtar Lubis atau Jakob Oetama. Terutama dalam memilih strategi perjuangan menegakkan demokrasi.
Perdebatan seperti itu kini tidak ada lagi di kalangan pelaku media masa. Tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan. Bahan yang dibahas juga habis –tidak ada lagi mahasiswa yang galak. Yang mestinya membahas pun –para wartawan profesional– sudah lelah. Atau takut pada bos pemilik media.
Gaya Pak Jakob adalah gaya yang ternyata lebih bisa diterima siapa saja –kecuali yang progresif.
Nyatanya Kompas menjadi raja media masa di Indonesia. Lalu menjadi raja toko buku: Gramedia. Raja hotel: Santika-Amaris. Dan banyak lagi.









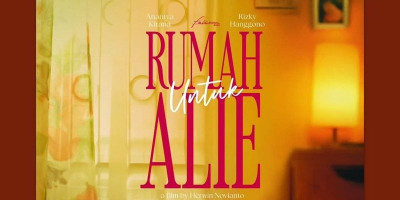






KOMENTAR ANDA