INI soal 2 triliun juga. Kalau dikumpulkan. Dan lagi tulisan ini pasti aman: tentang durian. Disenangi di gurun sekaligus di kolam. Tidak mengenal agama atau pun ras.
Dan lagi, durian bisa mengangkat nasionalisme.
Seperti yang dilakukan Theng Ah Khiong ini. Ia termasuk yang tidak rela Indonesia kalah oleh Malaysia –dalam hal durian.
Sudah lebih tujuh tahun ia keliling Indonesia. Dari hutan ke hutan: mencari durian unggul di semua pulau.
Akhiong, nama panggilannya, lantas memutuskan untuk membuat lahan riset durian: 40 hektare. Lokasinya di Ogan Ilir, dekat-dekat yang Rp 2 triliun itu.
Di situlah Akhiong menanam 60 jenis durian paling unggul dari seluruh Indonesia. Tanaman itu kini sudah berumur 2 tahun. Serius sekali. Biaya pemeliharaan dan risetnya mahal sekali: Rp 125 juta/hektare sampai berbuah nanti.
Akhiong pun mengambil kesimpulan: durian terbaik adalah dari Kalimantan Barat. Khususnya dari hutan sekitar Entikong –dekat perbatasan dengan Serawak, Malaysia.
Juga: dari Bangka.
Lalu: dari Papua.
Akhiong begitu tersinggung kalau ada yang menulis –tidak perlu saya sebut nama penulisnya– durian terbaik adalah Musang King dari Malaysia. Saya sampai tersipu-sipu.
Lebih tersipu lagi kemarin malam, Minggu lalu. Ketika ada paket satu kotak datang ke rumah saya. Saya pikir itu ancaman bom. Ternyata kotak itu berisi durian. Masih utuh dengan kulitnya. Banyak sekali.
Pengirimnya: Akhiong!
Saya harus menghabiskan semua itu. Biar kapok. Biar kalau menulis tidak ngawur. Biar tahu begitu banyak durian Indonesia yang lebih enak dari Musang King.
Kotak itu datangnya dari Bangka. Dikirim dengan pesawat Garuda. Saya lupa menghitung berapa biji. Tiap biji beda rasa, beda nama, beda agama –ups beda teksturnya.
Rupanya Akhiong begitu emosinya sampai mengumpulkan semua jenis durian Bangka terbaik. Ada yang warna dagingnya tembaga –itulah durian Tembaga. Ada yang warnanya putih sekali –durian kapas.
Yang paling dijagokan adalah yang warna dagingnya keemasan: itulah durian Tupai Chong.
"Apakah itu yang di Malaysia disebut Tupai King?" tanya saya.
Akhiong tersinggung.
Ia tidak rela Tupai Chong-nya Bangka disejajarkan dengan Tupai King-nya Malaysia. "Penggunaan kata Tupai di Malaysia itu yang justru meniru Bangka. Istilah Tupai King di Malaysia baru ada dua tahun ini. Tupai Chong sudah puluhan tahun," ujarnya.
Saya pun tidak sabar: ingin segera membuka Tupai Chong itu.
Tapi makan durian sendirian? Tidak seru. Saya harus tahan emosi. Saya membuat jadwal: habis Isya. Saya undang teman durian saya: Liong Pangkey. Yang di hatinya, di jantungnya, di darahnya hanya ada satu mimpi: durian. Ia orang Gorontalo yang sudah lama di Surabaya.
Sebenarnya saya ingin undang beberapa teman lagi. Tapi saya takut justru saya bisa tidak kebagian.
Yang jelas saya tidak undang istri saya: punya komorbid. Tidak undang dua anak saya: benci durian. Azrul Ananda pernah pingsan di dekat durian. Waktu kecil. Waktu diajak jalan di dekat tumpukan durian di Singapura.
Maka kemarin malam itu, di bawah rindang pohon-pohon mangga di halaman, di depan studio gamelan, di bawah sinar bulan yang masih bulat terang, saya membuka si Tupai Chong. Buahnya kecil –hanya lebih besar dari 10 kepala tupai disatukan
Warnanya benar: keemasan.
Lalu saya pejamkan mata untuk mencicipinya. Ganti saya yang pingsan –seolah-olah. Sambil mengisap daging durian itu, pelan-pelan, khayalan saya ke Singapura, ke Malaysia, ke Vietnam, ke Thailand, ke Hainan: semua kalah. Warnanya, rasanya, manis-pahitnya, teksturnya, serba sempurna.
Kelemahannya: tidak ada.
Ups...ada. Di seluruh Bangka pohonnya hanya ada satu. Tinggal satu itu. Milik Pak Chong. Itulah sebabnya dinamakan Tupai Chong.
Pengakuan saya itu membuat emosi Akhiong reda. Ia pun mau bercerita banyak tentang petualangannya masuk hutan-hutan di banyak basis durian di Indonesia
Akhiong lahir di Palembang. Ayahnya kontraktor di perusahaan pengeboran minyak. Setamat SMA, ia kuliah di Jerman: teknik mesin. Sepuluh tahun Akhiong di Berlin. Sempat bikin usaha di sana.
Ia sangat terkesan dengan Jerman. Alamnya begitu dipelihara. Di kota Berlin saja ada tiga hutan kota. Di Jerman ia merasa bisa menyatu dengan alam.
Begitu pulang ke Palembang ia menyaksikan rusaknya alam. Ia juga tidak kerasan tinggal di kota seperti Jakarta atau Surabaya. Akhirnya ia pilih menetap di Papua. Di Jayapura. Di situ Akhiong memilih bisnis di perdagangan.
Ketika hidupnya sudah cukup secara ekonomi, Akhiong berpikir apa lagi yang bisa diperbuat untuk keunggulan Indonesia di bidang alam. Sebagai anak Palembang ia sangat durian-minded. Yang di Palembang, di masa kecilnya, durian hampir tidak ada harganya.
Waktu kecil itu, ketika diajak jalan-jalan ke Singapura, ia ikut ayah dan teman-teman sang ayah ke pusat penjualan durian di sana. Yang membuat ia kaget: harganya.
Di kampungnya durian begitu tidak bernilai. Di Singapura begitu mahalnya.
Itulah yang terus hidup di pikirannya. Pun sampai ia bawa ke Jerman. Biar pun sekolahnya teknik ia tidak berhenti memikirkan durian. Terutama soal beda harga tadi.
Sambil dagang, Akhiong pun mulai menyiapkan lahan untuk durian. Tapi bukan seperti waktu ia kecil. Ia harus melakukan riset. Harus dengan ilmu pengetahuan.
Tentu ribuan pohon durian yang ia tanam di lahannya di dekat Palembang itu. Tapi ia menyisihkan sebidang area untuk menanam durian unggulan dari seluruh Indonesia.
Tentu saya berdoa agar pandemi cepat selesai. Salah satu alasan saya: ingin ke lahan riset durian milik Akhiong itu. Sambil mampir ke rumah Heryanti, wanita 2 triliun itu.
Saya, tentu, juga ingin ke Bangka. Untuk bertemu dengan Pak Chong itu. ![]()








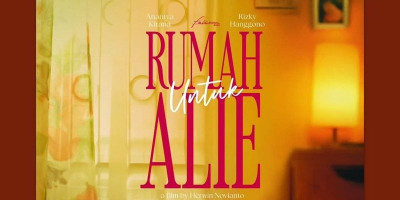






KOMENTAR ANDA