Ketika memasuki bulan Ramadan, kebiasaan berprotokol Covid sudah melekat. Kami merasa hidup normal --normal baru.
Tiap pagi tetap olahraga --olahraga Covid: pakai masker, cari yang bersinar matahari, dan jaga jarak. Termasuk di bulan puasa.
”Kok puasa-puasa olahraga satu jam?” tanya beberapa teman.
Jawab saya sama: saya ingat ayah saya. Yang di bulan puasa pun tetap ke sawah. Mencangkul. Sejak jam 6 sampai jam 10 pagi. Di bawah terik matahari. Dengan punggung telanjang.
Saya juga ingat waktu ayah pulang. Sambil memanggul cangkul di pundaknya. Betapa ayah saya itu terlihat lelah, haus, dan lapar. Lalu menggelar tikar di atas lantai --lantai rumah kami terbuat dari tanah.
Ayah pun tidur telentang di atas tikar itu. Tetap dengan celana ke sawah sampai di bawah lutut. Tanpa baju.
Saya lihat perutnya begitu kempes. Kulit perutnya seperti menempel di bagian dalam punggungnya. Begitu lelap tidurnya. Dengan kaki dan celana yang masih belepotan lumpur kering.
Ayah bangun ketika waktu zuhur tiba. Saat itulah baru cuci kaki. Lalu ganti celana dengan sarung. Ambil air wudu. Untuk salat zuhur.
Ayah lantas mengaji sampai asar tiba. Setelah salat asar ayah bersih-bersih pekarangan. Atau memperdalam parit dengan cangkul.
Olahraga saya di bulan puasa ini tidak ada artinya dibanding kerja keras ayah saya itu.
Setelah cucu-cucu boleh ke rumah, saya pun berpikir. Apa yang bisa saya lakukan dengan cucu-cucu itu.
Saya tawarkan untuk mengajari mereka Bahasa Mandarin. Mereka mau. Tentu kemampuan Bahasa Mandarin saya belum level untuk boleh mengajar. Tapi ini kan darurat.
Maka setiap jam 14.00 saya menjadi guru Mandarin untuk cucu-cucu saya. Selama 1,5 jam. Kurikulumnya saya sendiri yang menentukan. Bisa lebih tepat guna.
Ternyata yang tiga orang sudah mendapat pelajaran Bahasa Mandarin di Sekolah Ciputra. Saya tes asal-asalan, sudah tahu bahasa itu untuk tingkat dasar. Maka yang tiga orang lagi saja yang ikut pelajaran saya. Yakni mereka yang sekolahnya di Al Azhar International Surabaya.
Rumah saya menjadi seperti tempat kursus.
Di rumah kami tidak ada pembantu. Istri saya yang jadi pembantu. Mungkin pembantu termahal gajinya. Cuci pakaian, masak, belanja, dan menata rumah dia semua yang melakukan.
Itu sudah menjadi kebiasaan sejak dulu. Sudah biasa sibuk. Mungkin karena kami kawin dulu masih belum bisa membayar pembantu. Mungkin juga karena dia anak sulung dengan adik 11 orang.
Hanya sesekali Kang Sahidin masak sendiri --kalau ia lagi kangen masakan Sunda.
Salat tarawih pun kami berempat. Kang Sahidin yang jadi imam. Sabtu malam makmumnya lebih banyak: ke tambahan cucu saya, 6 orang.
Lebaran nanti kami sudah memutuskan: salat Idul Fitri di halaman rumah. Anak-cucu-menantu ikut serta. Kang Sahidin imamnya --saya yang akan khotbah.
Rasanya kami mulai merasa hidup normal. Istri saya tetap ke pasar tradisional. Dengan prosedur Covid. Pakai masker. Belanjanyi pakai uang pas. Tidak perlu berisiko menerima uang kembalian. Kalau uangnya lebih dia minta barangnya saja yang ditambah. Atau untuk deposito belanja berikutnya.
Awalnya memang kagok, kata istri saya. ”Ke pasar kok seperti musuhan dengan pedagang,” katanyi. Tapi sekarang sudah biasa.
Rasanya, setelah lebaran, kami siap untuk mulai hidup normal --normal baru itu.
Di Tiongkok hidup-normal-baru sudah berjalan normal. Saya hubungi teman-teman saya di sana. Kota-kota besar sudah benar-benar nyaris normal-baru. Semua sudah hidup lagi --kecuali bioskop, panti pijat, dan night club.
Memang tiba-tiba ditemukan penderita baru di Kota Wuhan. Lima orang. Umur di atas 70 tahun. Salah satunya 84 tahun.









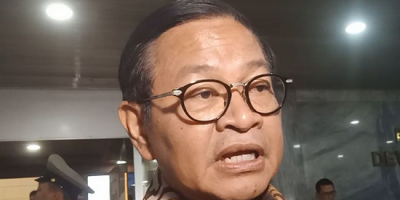





KOMENTAR ANDA